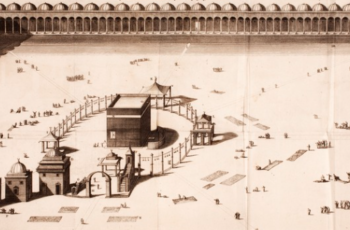JelajahPesantren.Com – Pluralisme agama selamanya tidak akan memperoleh kata sepakat. Ada yang begitu semangat membela dan mengusung konsep tersebut. Ada pula yang sama sekali menolak konsep itu, karena bertentangan dengan pemahaman mereka terhadap Islam. Di samping juga ada yang menerima konsep itu namun dengan batasan-batasan yang menurut mereka bisa ditolerir. Perbedaan tersebut dikarenakan perbedaan persepsi dan penafsiran terhadap ajaran Islam.
 Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, pluralisme biasanya dikategorikan ke dalam kajian teologi modern. Secara historis tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya pluralisme agama memang berasal dari disiplin ilmu teologi. Mengenai hal itu, perlu diperhatikan bahwa konsep teologi dan fakta historisnya justru bertentangan dengan ide pluralisme yang mengandung toleransi tingkat tinggi. Dalam bentangan sejarah teologi mana pun, utamanya Islam, perpecahan dan perbedaan selalu mengemuka dan mencuat. Perbedaan tersebut, khusus dalam teologi Islam, menjadikan mereka gencar melakukan pelabelan terhadap kelompok lain. Teolog Mu’tazilah, Hanabilah, dan Ahl Al-Sunnah tidak pernah akur dan saling mengecam. Qadariyah dan Jabariyah tidak pernah sepakat dalam persoalan perilaku makhluk. Tidak heran jika al-Ghazali mengecam mereka yang suka mengkafirkan kelompok lain dan menyebut mereka sebagai kelompok yang meng-kapling surga. Al-Ghazali menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim al-Baijuri dalam Kifayat al-‘Awam:
Terlepas dari berbagai perbedaan tersebut, pluralisme biasanya dikategorikan ke dalam kajian teologi modern. Secara historis tidak bisa dipungkiri bahwa munculnya pluralisme agama memang berasal dari disiplin ilmu teologi. Mengenai hal itu, perlu diperhatikan bahwa konsep teologi dan fakta historisnya justru bertentangan dengan ide pluralisme yang mengandung toleransi tingkat tinggi. Dalam bentangan sejarah teologi mana pun, utamanya Islam, perpecahan dan perbedaan selalu mengemuka dan mencuat. Perbedaan tersebut, khusus dalam teologi Islam, menjadikan mereka gencar melakukan pelabelan terhadap kelompok lain. Teolog Mu’tazilah, Hanabilah, dan Ahl Al-Sunnah tidak pernah akur dan saling mengecam. Qadariyah dan Jabariyah tidak pernah sepakat dalam persoalan perilaku makhluk. Tidak heran jika al-Ghazali mengecam mereka yang suka mengkafirkan kelompok lain dan menyebut mereka sebagai kelompok yang meng-kapling surga. Al-Ghazali menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Ibrahim al-Baijuri dalam Kifayat al-‘Awam:
“أسرفت طائفة فكفروا عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف العقائد بالأدلة التي حرروها فهو كافر. فضيقوا رحمة الله الواسعة وجعلوا الجنة مختصة بطائفة يسيرة من المتكلمين”.
Satu aliran teologi telah bertindak melampaui batas. Aliran ini mengkafirkan kebanyakan muslim. Sebab dalam pandangannya, siapa yang tidak mengetahui akidah (yang berjumlah 50) beserta dalīl-dalīl yang ditetapkan oleh mereka diklaim sebagai orang kāfir. Aliran semacam ini mempersempit rahmat Allah yang sangat luas dan mengklaim surga hanyalah milik segelintir kelompok teolog saja.
Pandangan teolog yang “demikian sempit” bisa dimaklumi, sebab mereka hanya memahami agama dalam tataran syariat saja. Mereka tidak sepenuhnya, untuk tidak mengatakan tidak sama sekali, memahami hakikat sebuah agama. Berbeda dengan kelompok sufi yang melihat agama dari sisi hakikatnya, sehingga mereka lebih toleran dan menghargai perbedaan pendapat maupun perbedaan agama. Ali Harb, dalam Naqd al-Haqiqat, juga mempertegas bahwa perspektif sufisme tampak jauh sekali lebih terbuka (inklusif) dibandingkan dengan perspektif filsafat, apalagi perspektif fikih, dalam menghargai orang lain.
Ahmad Amin juga sepakat dengan statement “perspektif sufisme lebih inklusif dibanding perspektif lain”. Ia mengatakan bahwa sufisme bukanlah sebuah aliran, sehingga seorang sufi bisa lintas aliran bahkan lintas agama. Sufi bisa dari kalangan Syi’ah, Sunni, Mu’tazilah atau dari kalangan Kristen, Yahudi dan sebagainya. Hal ini, dalam analisa Amin, disebabkan para sufi secara keseluruhan (walaupun kebanyakan mereka tidak mengungkapkannya baik secara lisan maupun tulisan) meyakini konsep wahdat al-wujud, yakni sebuah paham kesatuan wujud (Allah swt) dan semua makhluk adalah replika dari Allah swt.
Seyyed Hossein Nasr lebih detail dalam menjelaskan inklusifitas sufisme. Nasr membuat sebuah teori yang dikenal dengan teori roda sepeda; yang terdiri dari pinggiran roda atau ban, jari-jari, dan as (pusat). Pinggiran roda mencerminkan tataran syariat, jari-jari mencerminkan thariqat, dan as adalah hakikat. Nasr menyimpulkan bahwa seseorang yang semakin jauh dari titik pusat, dipastikan ia semakin renggang, rentan konflik dan eksklusif. Sebaliknya, semakin ia dekat terhadap pusat, pasti ia semakin menyatu dan lebih inklusif.
Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa secara historis mungkin benar bila dikatakan pluralisme merupakan turunan dari teologi. Akan tetapi secara konseptual, saya lebih setuju bahwa pluralisme agama adalah turunan dari disiplin ilmu tasawuf. Sehingga, dalam hemat saya, seseorang tidak boleh mengaku dirinya seorang pluralis bila ia belum menjadi seorang sufi. Sebab hanya sufi-lah yang benar-benar pluralis. Sementara teolog, faqih, atau yang lain hanya bisa mendapat predikat seorang toleran, bukan seorang pluralis. Hal ini bila pluralisme dimaknai sebagai “paham yang mengatakan bahwa semua agama benar, sebab agama-agama tersebut hanya berbeda nama dan bentuk saja, sementara tujuannya sama”. Definisi semacam ini sama persis dengan pernyataan Sufi pelopor pluralisme, Al-Hallaj (244 – 309 H): “Hai anakku, agama itu milik Allah, Dia telah menetapkan agama bagi setiap kelompok dan mereka tidak memiliki kemampuan untuk memilihnya, bahkan telah dipilihkan untuknya. Karena itu, barang siapa menyalahkan apa yang dianut oleh golongan itu, berarti dia telah menghukumi golongan tersebut menganut agama atas upayanya sendiri. Ketahuilah! Agama-agama Yahudi, Nashrani, Islam, dan sebagainya adalah julukan yang berbeda-beda dan nama yang berubah-ubah, padahal tujuannya tidak berbeda maupun beraneka”.